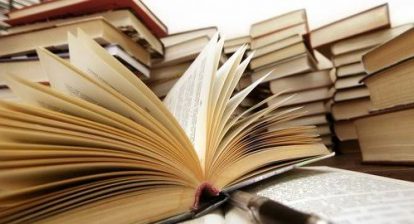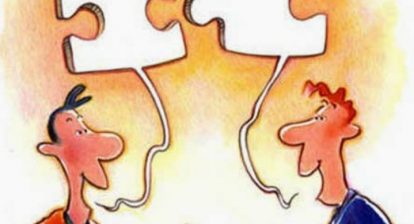Saat ini manusia memasuki era revolusi digital dan internet. Di mana peradaban manusia dibangun atas serangkaian teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih. Roger McNamee investor pertama Facebook menyatakan kesaksiannya bahwa pada 50 tahun pertama Silicon Valley, industri teknologi terkemuka di dunia ini membuat produk baik itu hardware maupun software yang dijual ke publik.
Itu menjadi model bisnis yang sederhana. Namun, sepuluh tahun terakhir perusahaan teknologi besar di Silicon Valley tidak lagi menjual produk, tetapi menjual penggunanya. Aza Raskin penggagas Firefox & Mozilla Labs pun mengatakan bahwa karena pengguna memakai sosial media secara gratis, maka pengiklan-lah yang sejatinya membayar layanan sosial media yang kita gunakan. Dengan kata lain model bisnis sosial media adalah menarik sebanyak mungkin pengiklan memasang produknya, di mana pasar iklan tersebut tak lain adalah para pengguna media sosial di seluruh dunia.
Secara garis besar, perusahaan teknologi ini bekerja untuk mencapai tiga visi utama. Pertama, tujuan keterikatan yaitu untuk meningkatkan penggunaan Anda untuk terus memakainya. Kedua, tujuan pertumbuhan dengan membuat Anda kembali dan mengundang sebanyak mungkin teman dan ketiga tujuan periklanan yaitu untuk memastikan bahwa karena semua itu terjadi, mereka menghasilkan uang sebanyak mungkin dari iklan. Di satu sisi, pengguna sosial media merasakan bahwa aktivitasnya memakai pelbagai platform sosial media itu menguntungkan karena pemakaiannya gratis dan tampilan dan pelbagai fiturnya menarik bisa berinteraksi secara menyenangkan dengan banyak orang yang tak terbatas. Namun di sisi lainnya, perusahaan teknologi memanfaatkan data pribadi, serta riwayat aktivitas pengguna tersebut sebagai sebuah aset yang bisa diolah menjadi profit. Ada pepatah kuno, “If you’re not paying for the product, then you are the product.”.
Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest Reddit, Snapchat dan lainnya model bisnis perusahaan mereka adalah memikat sebanyak mungkin pengguna dan membuat pengguna selama mungkin terpaku di layar komputer, smartphone maupun tablet. Seberapa lama waktu pengguna bisa dihabiskan untuk berinteraksi di platform media sosial tersebut semakin besar data yang bisa diserap.
Mereka berlomba-lomba menarik pengguna untuk membuat pengguna merasakan kenyamanan menghabiskan waktunya untuk berselancar di media sosialnya. Selama itu pula pengguna tanpa sadar dikendalikan pola pikir dan persepsi, hingga perilakunya tentang segala hal. Shoshana Zuboff, professor emeritus Harvard Business School, menyatakan bahwa media sosial saat ini menjadi bisnis yang diimpikan seluruh perusahaan. Media sosial memiliki keunggulan berupa jaminan keberhasilan pada iklan-iklan yang dipasang di beranda mereka. Dengan kepemilikan data pengguna yang besar, maka media sosial menyajikan prediksi-prediksi yang akurat tentang segala hal, dan bisa menopang kepastian jalannya suatu bisnis. Kepastian tersebutlah yang menjadi uang. Dengan kata lain, media sosial mampu mempengaruhi persepsi dan perilaku penggunanya diarahkan kepada keinginan si pengiklan.
Media sosial menjadi jenis lokapasar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Media sosial juga disebut sebagai kapitalisme pengawasan data pengguna. Bentuk kapitalisme baru yang mengambil profit sebesar-besarnya dari jutaan pengguna tanpa jejak dan tak terbatas. Jeff Seibert mantan eksekutif pendiri Twitter menjabarkan aktivitas seluruh orang yang berselancar di internet diawasi, dilacak, diukur, dipantau dan direkam dengan hati-hati.
Semisal seberapa lama gambar yang dilihat dan seberapa lama waktu keterlibatan pada sesuatu. Mereka tahu saat orang kesepian, depresi, gembira, bahagia, dan keseluruhannya. Perusahaan teknologi memiliki lebih banyak informasi tentang kepribadian seseorang daripada yang pernah dibayangkan dalam sejarah manusia.
Senada itu, Sandy Paraklas, mantan manajer operasi Facebook dan Uber, pun mejelaskan bahwa segala rekaman aktivitas pengguna dimasukkan ke sistem big data yang dikelola kecerdasan buatan. Sistem ini terus memproduksi prediksi yang semakin membaik karena selalu update sesuai aktivitas pengguna media sosial dalam rentang detiknya. Dengan big data, sosial media mampu membuat prediksi bahkan manipulasi penggunanya.
Contohnya cara hidup generasi Z yang mengenal sosial media sejak usia remaja telah dimanipulasi dan diarahkan lebih mementingkan aktivitas di internet ketimbang dunia nyata. Dengan demikian media sosial yang sebelumnya digadang menghubungkan orang-orang yang terpisah jarak, justru kini berdampak pada menjauhkan komunikasi langsung ke komunikasi tidak langsung lewat ruang media sosial yang yang sarat manipulasi dan didanai oleh kepentingan bisnis, kelicikan dan penipuan.
Media sosial dibangun atas teknologi persuasif yang diterapkan secara ekstrem untuk mengubah perilaku seseorang. Di mana pengguna akan terus berselancar dengan jari-jarinya terus mengeklik dan menggeser layar dan selalu muncul hal baru dan menarik. Dalam psikologi ini disebut penguat intermiten positif. Kita tak tahu kapan atau apakah kita akan mendapatkannya. Media sosial bukan hanya ingin membuat pengguna menghabiskan banyak waktu saja tetapi secara tidak sadar ia sudah masuk ke batang otaknya dan menanamkan kebiasaan secara tak sadar ke dalam diri si pengguna. Agar secara tidak sadar otak diprogram untuk selalu melihat ponsel atau melihat notifikasi yang mungkin berisi hal menarik untuk dibuka. Teknologi media sosial didesain dengan teknik persuasif seperti itu.
Sosial media itu adalah narkoba. Kita mempunyai perintah biologis dasar untuk terhubung dengan orang lain. Itu secara tidak langsung memicu pelepasan dopamin dalam tubuh kita. Jadi tak bisa diragukan lagi kalau sosial media yang mengoptimalkan hubungan antar orang ini akan memiliki potensi kecanduan. Di antara dampak buruk kecanduan media sosial antara lain: Kesehatan mental pengguna; Berita palsu (hoax) yang cepat menyebar; Membuat remaja frustasi dan depresi; Pengguna diarahkan oleh perusahaan teknologi sehingga tidak mempunyai preferensi sendiri, bahkan preferensi diarahkan oleh platform : misalnya harus cantik dengan operasi plastik;Pengguna dibombardir oleh iklan-iklan perusahaan komersial; Pengguna dibuat halusinasi dengan harus selfie dan dipercantik dengan aplikasi agar bagus saat di upload sehingga mendapat like, pujian dari pengguna lain; Cara berpolitik yang tidak sehat.
Maka untuk menanggulanginya dibutuhkan literasi digital. Istilah literasi digital dikemukakan pertama kali oleh Paul Gilster (1997) sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ia mengemukakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, seperti akademik, karier, dan kehidupan sehari-hari. Seseorang harus memiliki kemampuan dalam penguasaan perangkat teknologi digital, dengan harapan individu tersebut sudah memiliki keterampilam literasi digital
Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
Guntur Rammadan, Universitas Pamulang