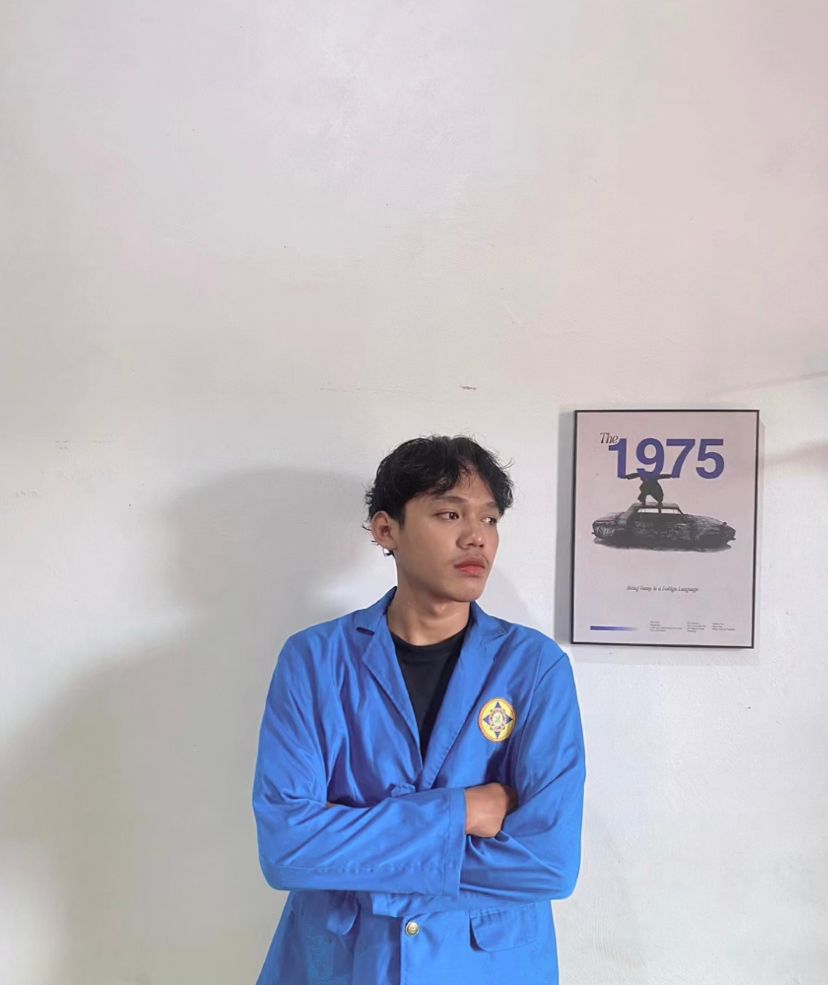Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia telah menjadi fondasi yang mengikat keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa dalam satu kesatuan. Namun, dalam praktik sosial-politik kontemporer, terutama di era digital yang sarat dengan arus informasi cepat dan tak terbendung, nilai-nilai Pancasila seringkali hanya menjadi slogan formalistik yang kehilangan makna dalam tindakan nyata. Generasi muda sebagai aktor utama masa depan bangsa perlu lebih dari sekadar menghafal lima sila; mereka harus mampu menginternalisasi dan mengaktualisasikannya dalam perilaku sehari-hari, baik di ruang fisik maupun digital.
Di tengah masifnya penggunaan media sosial, kita menyaksikan paradoks ideologis. Di satu sisi, media digital menjadi ruang untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Namun di sisi lain, ia juga menjadi medium subur bagi ujaran kebencian, polarisasi politik, dan radikalisme yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila ketiga (Persatuan Indonesia). Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan aktual bukanlah pada relevansi Pancasila, melainkan pada komitmen kolektif dalam mewujudkannya sebagai etika hidup berbangsa.
Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan kembali kesadaran ideologis mahasiswa. Namun, pendekatannya harus adaptif dan kontekstual. Tidak cukup hanya dengan ceramah normatif atau hafalan sila; pembelajaran harus dikaitkan dengan realitas sosial-politik kontemporer dari isu korupsi, intoleransi, hingga krisis lingkungan dengan mempertanyakan, bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi solusi dalam menghadapi problem tersebut?
Misalnya, sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” menuntut praktik demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural. Namun, kenyataannya, banyak proses politik yang justru jauh dari semangat musyawarah dan keadaban publik. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus berani mengkritisi kondisi tersebut secara konstruktif, dengan tetap berlandaskan pada prinsip Pancasila, bukan sekadar mengikuti arus opini mayoritas.
Selain itu, Pancasila bukanlah ideologi tertutup. Ia bersifat terbuka dan progresif, sehingga dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman, asalkan tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Karena itu, dalam era globalisasi, Pancasila harus tampil sebagai etika publik yang mampu menjembatani modernitas dengan nilai-nilai lokal. Kita tidak perlu meniru sepenuhnya sistem luar negeri jika kita memiliki dasar ideologi yang kokoh. Namun, kita juga harus siap menyerap nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sejauh tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa.
Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab historis untuk tidak membiarkan Pancasila sekadar menjadi teks konstitusional yang hampa makna. Ia harus menjadi napas dalam bertindak, berbicara, dan berpikir. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri: sudahkah kita menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam menghadapi perbedaan, menolak hoaks, bersikap adil, dan memperjuangkan kebenaran?
Dengan demikian, internalisasi Pancasila bukan hanya tugas negara atau institusi pendidikan, tetapi tanggung jawab moral setiap warga negara, khususnya kaum muda. Di tangan kita, Pancasila bisa tetap hidup dan menjadi suluh yang menuntun bangsa Indonesia menuju peradaban yang adil, damai, dan berkeadaban.
Nama: Muhamad Raya Kusuma
Nim: 241092150016
Kelas Administrasi 002